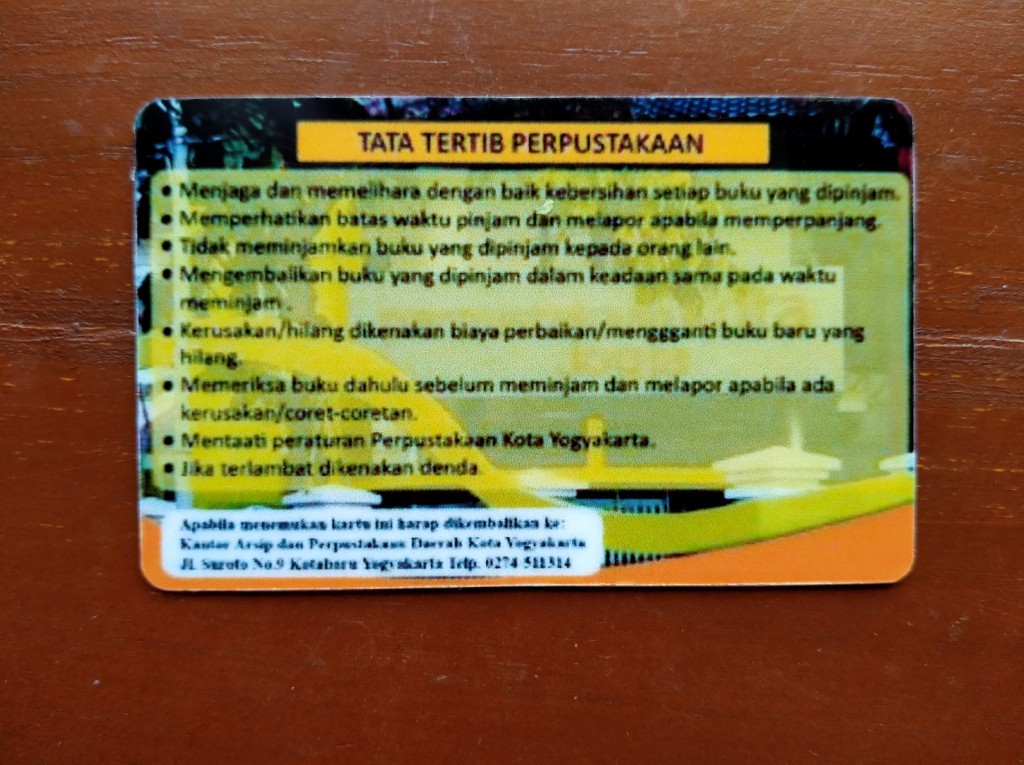Sebagai manusia dengan komponen psikologis yang (relatif) normal, tak jarang aku mempertanyakan posisiku di masyarakat. Aapakah aku telah menjadi bagian yang berfungsi dan memberikan apa yang aku bisa dan miliki untuk kemajuan bersama, atau aku hanya sekadar parasit yang kerjanya hanya menyerap sumber daya di sekitarku untuk memenuhi kebutuhan pribadiku sendiri?
Jadi ketika salah satu agen dari SOS Children Village melakukan sosialisasi program mereka padaku di sebuah pusat perbeanjaan sekitar setahun yang lalu, aku secara antusias mendaftarkan diri sebagai donatur tetap.
Mengutip penjelasan dari website mereka:
SOS Children’s Villages adalah organisasi sosial nirlaba non-pemerintah yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua kebutuhan utama mereka, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang.
Besaran donasi yang minimal program mereka adalah Rp. 150.000,-
Anggapan atas besar atau kecilnya jumlah tersebut tentunya tergantung pada siapa yang kita tanya.
Bagiku jumlah tersebut cukup besar untuk dikeluarkan setiap bulan. Apalagi aku memiliki manajemen keuangan yang bisa dibilang kacau, dengan pembelian impulsif now and then yang memperparah keadaan. Jadi meskipun di satu sisi aku merasa senang dan “penuh” karena berkontribusi positif bagi kehidupan anak-anak Indonesia yang membutuhkan, di sisi lain tak jarang aku merasa berat dan kesal melihat angka Rp. 150.000,- melayang otomatis melalui sistem autodebet dari rekeningku.
Selama beberapa bulan terakhir berulang kali aku mempertimbangkan untuk berhenti sama sekali dari program donasi tersebut. Dan berulang kali pula keputusanku tertunda karena perasaan bersalah pada anak-anak yang wajahnya saja belum pernah kujumpai langsung.
Lalu puncaknya adalah November ini ketika keperluanku sedang tinggi, angka di rekeningku membuatku membulatkan keputusan untuk menghentikan donasi bulananku. Jadi aku menghubungi pihak SOS Children Village melalui nomor 021-22785534.
Mereka menerima keputusanku untuk menghentikan donasi dengan terbuka, namun disertai perkataan manis yang menggambarkan apresiasi mereka atas kontribusiku selama ini dan perasaan sedih karena harus “berpisah” denganku. Sebagai orang yang mempelajari psikologi, aku menyadari betul taktik yang mereka gunakan. Menurutku kata-kata yang mereka gunakan dirangkai dengan apik, membangkitkan perasaan hangat atas apresiasi mereka dan perasaan bersalah karena menghentikan donasi dalam porsi yang pas.
Kemudian ada sebuah plot twist yang membuatku menyesal tidak menelepon dari bulan kemarin-kemarin:
Rupanya SOS Children Village menyediakan alternatif besaran donasi yang lebih ringan. Saat mendaftar dan juga melakukan riset di web mereka, aku hanya menemukan angka Rp. 150.000,- sebagai jumlah minimal dan beberapa jumlah lain yang lebih besar dari itu.
Pihak SOS Children Village memberikan tawaran angka donasi sebesar Rp. 50.000,-
Dengan sedikit kesal (karena sebelumnya aku kira pilihanya hanya minimal Rp. 150.000,- atau tidak sama sekali) dan juga gembira karena aku tidak harus menghentikan kontribusiku sama sekali) aku menerima tawaran tersebut.
Jadi mulai bulan Desember nanti aku tidak akan lagi gigit jari karena angka autodebet yang tinggi sehingga bisa benar-benar “menikmati” kontribusi kecilku bagi masyarakat. Ini juga menjadi wake up call bagiku untuk mengatur keuanganku dengan lebih baik sehingga dapat berkontribusi lebih besar lagi.
Sebagai penutup, aku mengajak siapapun yang membaca postingan ini untuk melakukan donasi bagi SOS Children Village. Terlalu banyak anak yang membutuhkan uluran bantuan kita, sayangnya terlalu sedikit orang yang peduli bahkan hanya untuk mempertimbangkan memberi donasi satu kali. Jadi jika kita bisa melakukan donasi rutin, meskipun julahnya “tidak seberapa”, pasti akan sangat berguna bagi mereka. Semakin banyak orang yang berhasil kita ajak, semakin banyak orang yang kita bantu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SOS Children Village Indonesia dapat didapatkan melalui:
KONTAK MEDIA
Fund Development & Communication
Jl. Jati Padang Utara No.13
Jakarta 12540 – Indonesia
Telp. 021-22785534
kontak@sos.or.id
P.S. Sejauh yang aku tahu untuk pendaftaran tidak bisa dimulai dari Rp. 50.000,-, jadi tetap harus dimulai dari Rp. 150.000,-. Tetapi untuk bulan selanjutnya bisa dicoba untuk menghubungi mereka untuk melakukan penyesuaian besaran donasi.